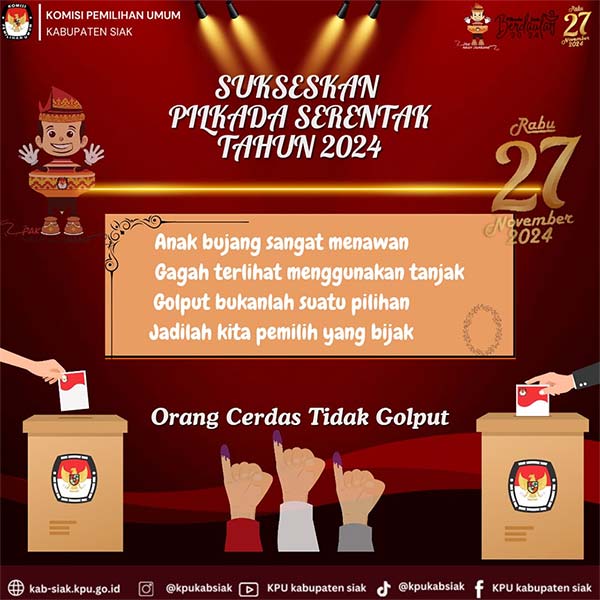(RIAUPOS.CO) — Mencuat sebuah berita di sebuah warung di kaki gunung. Berita itu dibawa seseorang dengan tas punggung besar dan jaket tebal pelindung tubuhnya yang juga besar. Berita itu membuat kampung jadi gempar. Tersebar dari warung hingga rumah warga yang letaknya sangat jauh di ujung. Aku tidak serta duduk di warung itu. Rumah di ujung berdinding kayu adalah tempatku menguping pembicaraan yang belum layu dan ramai dibicarakan.
Hari ke delapan aku tak menapakkan jejak di tanah depan rumah. Kukunci pintuku rapat dan menghilang dari orang-orang yang barangkali ramah. Tidak akan ada yang mengetuk pintu atau menggerutu jika tak bertemu denganku. Sebab tak seorangpun mau tahu tentang aku. Termasuk orang berbadan besar tadi, si pemberi kabar yang membuat gempar.
Kau tentu tak lagi sabar tentang apa yang digemparkan. Tentu ada sesuatu atau seseorang yang menjadi sumber semuanya. Bacalah, dan satu kata pun jangan kau lewatkan. Akan kuceritakan dengan pelan, sebab ia di sini sekarang dan sedang tidur di atas dipan. Seorang yang gila. Dan buta.
Cahaya dari api lilin bergerak ditiup angin tipis yang masuk lewat celah jendela yang tidak pas ukurannya. Aku menduga malam ini akan turun hujan, sebab guruh seolah suara langit yang hendak runtuh. Kuambil selimut tua yang warnanya putih kecoklatan di tepi dipan. Kutarik dan kubalut seluruh badan. Kupejamkan mata setelah berdoa semoga malam ini tuhan berikan mimpi yang berbeda. Aku sangat berharap sesekali aku bisa merasa bahagia meski hanya di mimpi saja. Rasa sedih dan sepi belasan tahun menggerayangi-sejak anakkku satu-satunya pergi mendaki dan tak kembali-bahkan dalam mimpi. Hidupku dicap sebagai sesuatu yang malang oleh semua orang.
Dinding depan tiba-tiba berbunyi. Deraknya terdengar seperti seseorang sedang bersandar. Kubuka mata seketika. Khawatir jika nanti pintu tiba-tiba dibuka, seseorang masuk dan mendapatiku yang sebatang kara dan tak berdaya. Bisa jadi ditusuknya aku dengan belati lalu pergi membawa apa saja barang berharga yang tersisa. Semakin hari kusaksikan orang-orang semakin gila. Ya, semakin banyak orang gila.
Aku duduk dan menyibakkan selimut buruk. Berjalan aku ke pintu dan kuintip lewat celahnya yang sebesar kurma. Benar seseorang sedang bersandar dan mendekap lutut dengan gemetar. Aku ingin membukakan pintu, tapi ketakutan membuat keberanianku gentar. Sementara awan berhembus semakin kencang membuat berisik daun-daun di pohon besar. Terdengar suara petir menggelegar. Dan suara pekikanku sampai ke luar.
Kututup mulut segera dan kembali menyematkan mataku di lubang yang sama. Orang di luar sadar bahwa ada suara manusia yang ia dengar. Ia meraba-raba dinding. Aku di dalam rumah merasa merinding. Sebab ketakutan sudah menjelma sangat luar biasa. Apalagi setelah kulihat di kedua matanya ada yang salah. Kedua mata itu mengalirkan darah.
Hampir sekali lagi aku berteriak. Tapi pemandangan ngeri itu membuatku tersedak.
Ia mengetuk apa saja yang menurutnya bisa diketuk. Tapi ia tidak memanggil siapa-siapa. Hanya mengetuk saja. Sedangkan aku di dalam hanya diam membatu.
Lama sekali hingga akhirnya kuputuskan untuk membukakan pintu, membiarkannya masuk, dan membimbingnya ke dipan untuk duduk. Selanjutnya, ia hanya mengangguk sebanyak yang ia mampu. Kupikir itu adalah tanda terimakasih untukku.
Ia menggeser duduknya ke belakang, sepertinya mencari dinding untuk bersandar. Lagi-lagi didekapnya lutut. “Kau kedinginan?” tanyaku sembari mengambilkannya selimut.
Bekali-kali ia mengangguk.
Kuambilkan segelas air putih dari teko besi yang terletak di samping panci. Kuberikan ke tangannya dan ia menghabiskannya sebentar saja. Lalu ia minta gelas diisi berulang kali. Kupikir tentu ia sudah berjalan jauh sekali. Atau berlari?
Baju kaus yang ia pakai begitu bau, terlihat lusuh, dan kumuh. Dalam cahaya lilin yang tidak seberapa, kulihat di tangannya membekas goresan-goresan luka. Dari bajunya yang robek samar-samar kulihat punggungnya biru memar. “Kau kenapa?” tanyaku lagi.
Ia menarik selimutnya lebih erat, menyelimuti tubuhnya rapat-rapat. Kakinya bergerak-gerak ke arah luar mengusirku. Aku beranjak, tapi tak banyak, aku masih duduk di dipan itu. Ia tahu. Dihentakkannya kaki dan degup jantungku dalam waktu yang sebentar tiba-tiba berhenti.
Aku pergi. Berdiri dan duduk di kursi. Kuperhatikan mata berdarah itu betul-betul sudah tertutup dengan rapat. Aku yakin sesuatu terjadi di sana, entah itu luka atau ia kehilangan kedua bola mata. Hal itu menjadi ngeri yang membuat bulu tengkukku berdiri.
Sebab ketakutan yang luar biasa, tak bisa kulepaskan perhatianku dari orang baru yang tak kutahu namanya itu. Kubiarkan dia diam di sana. Sampai akhirnya kedua tangan yang mendekap lutut berangsur terbelah dan kepalanya rebah. Ia tidur, kudengar ia mendengkur.
Pelan-pelan aku mendekat. Pelan-pelan tubuhnya kuluruskan untuk membuatnya lebih nyaman dan istirahatnya lebih lena. Lalu aku kembali duduk di kursi di samping meja. Kusandarkan kepala di atasnya dan tertidur begitu saja.
Di luar petir sesekali masih menggelegar dan hujan tentu saja turun tanpa rasa sabar.
Keesokan pagi kutemukan ia sudah kembali duduk di tepi dipan. Badannya digoyang-goyangkan. Entah untuk apa. Ketika ia dengar derit kursi dan suaraku-ketika meregangkan tubuh dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kepalanya kulihat bergerak-gerak, seperti mencari sumber suara yang sedari tadi ia tunggu. Kemudian ia memukul dipan dengan tangannya. Berulang-ulang.
Aku segera mendekat padanya dan bertanya, “Kau kenapa? Butuh bantuanku?”
Bibirnya melengkung ke bawah, wajahnya tiba-tiba berubah. Sedih sekali. Diarahkannya tangan yang seperti sedang mengais udara dan di arahkan ke mulutnya. Aku mengerti, ia pasti sudah lapar sekali.
Kulihat lauk di bawah tudung saji dan semangkuk nasi yang untung saja belum basi. Kupindahkan sebagian ke piring dan kuberikan padanya. Ia meraba-raba apa yang ada dalam piring di atas telapak tangannya. Kemudian ia tak peduli dan menghabiskannya dengan lahap sekali.
“Aku harus ke sungai, mencuci kain yang semalam kupakai. Aku juga harus mandi. Sementara itu kau duduk saja di sini. Aku sebentar akan kembali.”
Ia, entah mendengar atau tidak, tapi kuharap ia paham dan atas permintaanku ia tak menolak.
Aku pergi saja.
Jalan ke sungai mesti melewati warung kampung yang ada di kaki gunung. Di situ kudapati seorang bertubuh besar yang sedang minum teh sembari menyiarkan kabar. Jalan kupelankan sebab rasa penasaranku yang tak bisa kuelakkan.
“Orang itu berlari kencang sekali. Ia turun dari gunung seperti dikejar setan. Kusapa ia dengan suara yang aku yakin ia bisa mendengarnya. Tapi ia lewat saja. Aku yang turun sendirian agak ragu apakah itu manusia ataukah setan. Karena waktu itu langit sudah merah. Dan tentu saja maghrib akan tiba. Lalu…”
Aku tersandung sebuah batu dan berserakanlah baju-bajuku. Kotor ia sebab tanah coklat itu masih basah. Mata pengunjung warung tertuju padaku yang tertarung. Terdengar sedikit tawa di telinga, tapi kuabaikan saja. Tidak seorangpun membantu, sebab gelar ibu yang malang sudah melekat padaku setiap pagi sampai siang. Malang bagi mereka adalah penyakit menular dengan obat penawar yang langka.
Kukumpulkan pakaian dan memasukkannya ke ember yang kubawa dengan sangat pelan. Sesekali mata kuarahkan padanya dan sebuah tas besar di tonggak yang ia sandarkan. Warnanya campuran bercak coklat dan merah tua.
“Lalu, belum lagi aku tiba di posko pertama, kudapati dua orang sedang duduk di depan gua. Masing-masing memegang rokok yang menyala. Kusapa mereka. Lalu keduanya mendekat dan bicara tepat di depan muka. ‘Kau turun segera. Siapapun yang kau temui di bawah sana jangan sesekali kau coba membantunya. Atau kebaikanmu harus kau ganti dengan nyawa.’ Begitu katanya,” lanjut seseorang berbadan besar itu.
Orang-orang mulai curiga melihatku yang terlalu lama berada di sana. Segera kubuang muka dan berjalan ke sungai segera. Tiba-tiba cerita lanjutan dari orang itu membuatku urung mencuci pakaian. “Pertama kali aku sampai di kaki gunung ini, aku melihat seorang laki-laki di bawah pohon. Rombeng bajunya, dari kedua matanya mengalir darah yang masih segar tampaknya. Melihatnya yang benar-benar tidak berdaya, segera langkahku mendekat padanya, hendak menolong segera. Tapi aku ingat dengan ancaman dua laki-laki di atas tadi,” dem ikian akhir kabar yang bisa kudengar.
Langkah pelan tadi berubah menjadi langkah besar yang kecepatannya hampir sama dengan orang yang berlari. Kubuka pintu dan masih kudapati dia duduk di tempat yang sama. Kudengar ia terbatuk beberapa kali dan baru kusadari aku lupa memberinya minum tadi.
“Kau siapa?” tanyaku setelah air di gelas habis dteguknya.
“Dimana Rosalina? Rosalina bunga mawar yang merekah sempurna, dicabut mahkotanya,” dijawab tanyaku dengan sesukanya.
“Matamu kenapa?”
“Jangan kau lihat! Jangan kau lihat, bangsat!” ceracaunya.
Paham aku kalau yang sedang duduk di hadapanku adalah seorang gila.
Melihat ia sudah mulai bisa kuajak bicara, menurutku aku sudah bisa mengelap tubuhnya. Mungkin setelah bersih nanti, ia jadi lebih tenang dan aku bisa kembali mengajaknya berbincang. Aku berjalan ke ember pakaian berniat mengambil sehelai untuk kubasahkan. Tapi aku terkejut luar biasa dan jantung di dada seperti akan copot dari tempatnya bergantung. Sebuah bola mata ada di dalamnya. Kupikir mungkin tadi terbawa serta ketika aku mengumpulkan pakaian yang berjatuhan di jalan.
Tapi kenapa sampai ada bola mata di sana dan tidak ada seorangpun yang menyadarinya?
Sebuah firasat melesat.
Ketika kurasa otakku tiba-tiba kacau, sementara orang yang duduk di dipan itu terus saja menceracau, kudengar pintu diketuk. Kudengar suara batuk.
Orang gila diam tiba-tiba.
Aku juga.
Di tanganku masih ada sebuah bola mata.
“Jangan lihat!” bisiknya pelan.*
Batusangkar, 23 Mei 2019