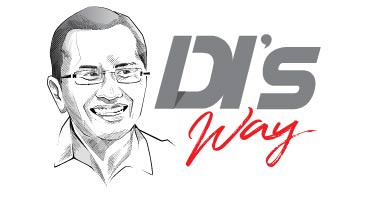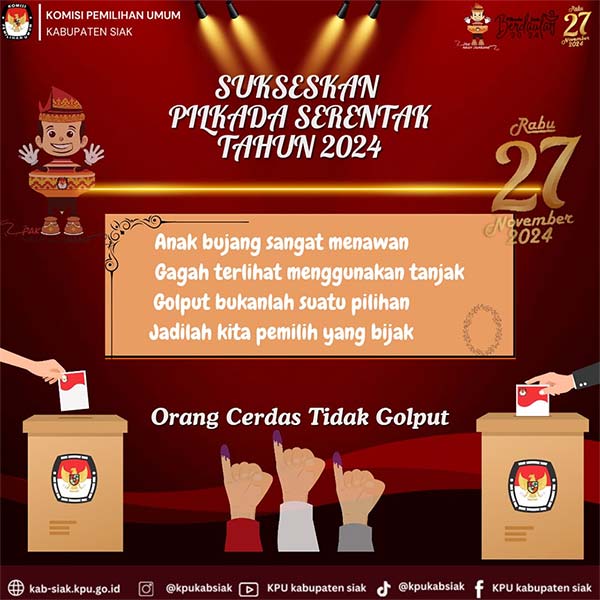(RIAUPOS.CO) — PERTUNJUKAN belum berjalan separuhnya. Wanita di sebelah saya ini menyodorkan tisu. Rupanya dia tahu saya mengusap air mata.
Padahal saya sudah berusaha serahasia mungkin. Saya jatuh terharu menonton Opera Rumah Susun ini. Yang menampilkan judul “Selendang Arimbi” itu. Dipentaskan di Atrpreneur Ciputra Kuningan, Jakarta. Sabtu kemarin. Saya dapat tiket pertunjukan yang jam 14.00.
Saya tidak menonton penampilan mereka yang pertama. Yang di tahun 2017. Waktu itu saya banyak pergi jauh. Saya tidak bisa membandingkan mana yang lebih menyenangkan. Yang jelas saya suka sekali menonton Selendang Arimbi. Saya sengaja menggunakan kata “suka” atau “tidak suka”. Saya menghindari kata “baik” atau “tidak baik”. Melihat karya seni sering harus subyektif.
Sekilas –dari promosinya– Selendang Arimbi ini seperti opera anak-anak. Tapi sutradara berhasil tidak membuatnya jatuh ke opera dolanan. Jalan ceritanya bisa dibilang “serius”. Kelemahan gerak tari anak-anak itu berhasil tertutup oleh kekolosalannya. Ada 200 anak dari tiga rumah susun Jakarta tampil di Selendang Arimbi: Rusun Pulo Gebang, Rawa Bebek, dan Daan Mogot.
Ketidaksempurnaan gerak dansa waltz-nya tertutup dengan gerak humor sang penari –terutama yang diperankan wanita berbaju merah itu. Gerak lucu itu justru menjadikan tari dansa itu sendiri lebih menghibur. Daripada, misalnya, menampilkan pedansa serius. Apakah wanita itu pedansa profesional yang diselipkan di antara anak-anak rusun?
Sutradara juga sering menyajikan banyak cerita di satu panggung. Tanpa terjadi kontradiksi. Misalnya saat teman-teman Arimbi membantu jualan selendang. Adegan jualannya justru diwujudkan dalam gerak di background. Adegan utamanya adalah tari lain. Yang menggambarkan kesibukan Taman Fatahillah Jakarta. Yang seperti itu membuat penonton merasa mendapat sajian menu beragam yang serasi.
Teknik berceritanya pun tidak kronologis –ciri khas lama opera anak-anak. Di Selendang Arimbi banyak dipakai teknik flashback. Atau flashfuture. Bahkan ending ceritanya pun sebuah flashback yang jauh. Yang membuat penonton tidak bisa menebak akhir dari cerita itu. Sungguh teknik penceritaan yang modern. Seperti novel yang diwujudkan dalam opera.
Ceritannya: Mega, anak miskin, mendapat beasiswa menjadi murid baru sanggar tari terkenal: Itnas Ibmira. Nama sanggar ini sendiri sudah menimbulkan imajinasi: merangsang penonton membacanya dari belakang. Pasti akan ada cerita tersembunyi dari nama itu. Tapi belum dibocorkan di awal sampai di tengah cerita. Ini bagian dari rahasia di akhir cerita. Bakat Arimbi menimbulkan kecemburuan murid lainnya. Termasuk anak manajer tari yang juga belajar di situ. Arimbi difitnah sebagai pencopet. Padahal uang banyak itu hasil jualan selendang d iTaman Fatahillah –dibantu teman-teman yang simpati pada Arimbi.
Fitnah itu terjadi justru seperti Arimbi jatuh tertimpa tangga. Arimbi lagi di puncak kesedihannya: ibunya suka menari sendirian setiap kali sang ibu ingat almarhum suaminya. Ternyata ketahuan: ibunya pernah punya cita-cita tinggi tapi kandas. Terpaksa jadi penjual selendang di kaki lima sepeninggal suami –untuk menghidupi Arimbi saat masih bayi.
Arimbi akhirnya juga tahu ibunyi sedang sakit paru. Dan kian parah. Sampai tidak bisa jualan. Justru di saat hampir berhasil menjadi penari utama di sanggar itu Arimbi memutuskan: berhenti menari. Meneruskan pekerjaan ibunyi: jualan selendang. Ingin bisa membawa ibunyi ke dokter.
Selendang tipe jumputan itu, di dunia nyata, ternyata produk penghuni rumah susun. Dijual di lobi Artpreneur sore itu. Di akhir cerita baru ketahuan: sang ibu dulunya kawin dengan penari juga. Lalu pindah ke Jakarta. Ingin karir tarinya melejit ke tingkat nasional. Seperti temannyi yang sudah lebih dulu sukses. Mereka sewa pondokan di rumah reot di bantaran sungai. Kena gusur. Dipindah ke rumah susun.
Nasib orang begitu berbeda. Teman akrabnyi sukses sekali. Kaya. Sampai punya sanggar tari sendiri. Bahkan bisa ke New York. Memperdalam tari di sana. Bertahun-tahun. Sampai-sampai sang ibu punya cita-cita: kalau punya anak akan diberi nama sama dengan temannya itu. Mengharukan: di akhir cerita sang ibu ditengok teman lamanya itu. Yang bernama Sinta Arimbi itu. Diantar oleh Sinta Arimbi, anaknya. Sang teman yang kemudian akan mengurus kesembuhan wanita itu.
Opera Selendang Arimbi memang bercerita di seputar rumah susun. Tapi jangan membayangkan ada adegan kumuh atau kotor atau semrawut di panggung. Di opera ini kemiskinan digambarkan tidak dengan kekumuhan. Sang sutradara kelihatan sadar sekali bahwa opera Selendang Arimbi akan ditonton golongan atas. Tempat pementasannya saja di Artpreneur Ciputra. Harga tiketnya saja Rp750 ribu. Yang termurah Rp350 ribu.
Sutradara berhasil membawa kesedihan dalam kegembiraan. Sebagai hiburan opera ini berhasil. Penonton memang ada yang tersedan seperti saya –tapi karena terharu. Bukan karena sedih. Muncul empati dalam keterharuan itu. Bravo. Selendang Arimbi bercerita tentang rumah susun bukan dari sisi kesedihannya. Tapi potensinya. Lalu memberikan harapan: bagaimana potensi itu menjadi keunggulan nyata.
Vero –mantan istri Ahok itu– juga tampil. Dua kali. Dan ikut jadi pusat perhatian penonton. Antara lain karena setting panggungnya dibuat begitu. Adegan yang dimainkan Vero relevan dengan kemampuannya: memainkan alat musik celo. Plot penampilan Vero pun sangat padu. Dan proporsional. Tidak sampai jatuh pada mentang-mentang Vero-lah produser dan penggagas Opera Rumah Susun ini.
Tiga anak Vero ada di Artpreneur itu: putra sulungnyi jadi penonton. Ia duduk –kebetulan– di sebelah saya bersama Olwen, teman akrabnya. Putri dan anak bungsunya ikut menjadi pemain. Opera Selendang Arimbi ini terasa lebih istimewa karena ada drama tersendiri di baliknya: sutradaranya meninggal tanggal 31 Oktober lalu. Justru ketika Selendang Arimbi tengah seru-serunya di tahap latihan.
Rita Dewi Saleh, sutradara itu, meninggal akibat sakit paru. Kanker paru. Adakah cerita sakit parunya ibunda Arimbi terinspirasi dari sakit yang dialaminyi sendiri? Video bagaimana Bunda Rita melatih anak-anak rumah susun ditampilkan sebelum opera. Termasuk saat melatih dari tempat tidurnya. Melatih sambil selang oksigen masih ada di lubang hidungnya.
Adegan video-video itu seperti dibuat menyatu dengan opera. Seperti intronya. Penonton menjadi sudah terharu sejak intronya itu. Saya sengaja menutup diri sebelum menonton opera Selendang Arimbi. Saya tidak mau membaca berita seputar itu. Tidak ingin tahu riwayatnya. Saya ingin menonton tanpa terpengaruh bahan-bahan yang tersedia. Saya ingin menonton sebagai penonton. Saya memang sempat bertemu Vero sebelum pertunjukan. Tapi saya tidak mau ngobrol soal Selendang Arimbi.
Saya juga bertemu dengan raja opera anak-anak masa lalu: ratu pop kita Titiek Puspa. Tapi saya hanya mendengarkan ledakan mimpinyi. Yang masih sangat jernih. Juga hanya untuk mengagumi kesehatannyi yang prima, kulit wajahnya yang tetap halus dan geraknyi yang masih enerjik. Di usianya yang 82 tahun. Saya juga ketemu Rina Ciputra dan Ibu Martha Tilaar yang mensponsori opera ini. Ada juga istri Gubernur DKI Anies Baswedan. Juga hanya untuk salaman. Sehari setelah menonton saya baru bertanya pada Vero. Tentang siapa nama sebenarnya pemeran Arimbi itu. Apakah dia benar-benar anak rumah susun.
“Nama anak itu Mega. Dari rumah susun Pulo Gebang,” ujar Vero.
Saya harus mengakui Opera Selendang Arimbi ini hasil kerja keras dan kerja cerdas. Juga wujud sebuah empati. Bagaimana 200 anak susun ditransformasikan ke Artpreneur Ciputra. Dalam sebuah opera kelas Artpreneur –bukan ‘opera untuk sebuah proyek pemda’. Rumah susun, di opera ini, bukan obyek. Tapi sekaligus subyek. Vero layak dapat bunga malam itu.***