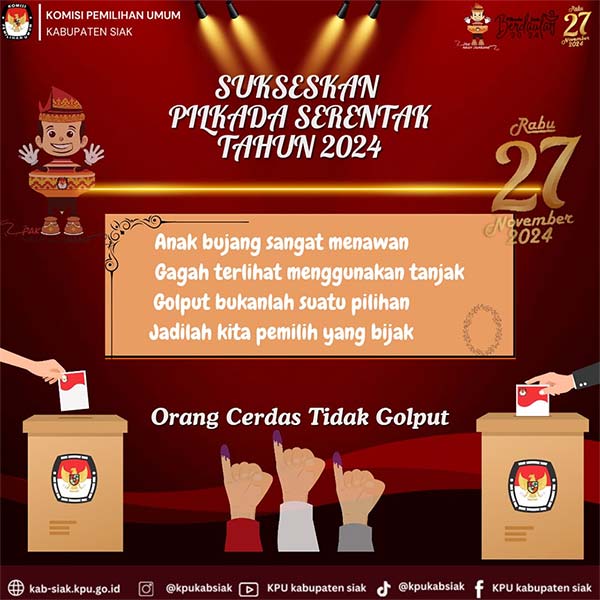Paradoks Antara Rakyat, Artis, dan Politisi
Konseptualisasi ruang publik (publik sphere) awalnya dikemukakan oleh Jurgen Habermas, seorang filsuf Mazhab Frankfurt. Menurut Habermas ruang publik adalah ruang di mana warganegara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka sehingga menjadi arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda. Arena ini secara konseptual berbeda dengan negara, yaitu tempat untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang bisa secara prinsip merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Selain itu, ruang publik secara konseptual juga berbeda dengan ekonomi resmi, yaitu bukannya tempat untuk hubungan pasar seperti penjualan dan pembelian, tetapi merupakan tempat untuk hubungan-hubungan yang berbeda-beda dan menjadi tempat untuk melakukan perdebatan dan permusyawaratan. Menurut Habermas, dalam ruang publik "private persons" bergabung untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama. Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat melalui publisitas. Tanggung jawab negara mensyaratkan bahwa informasi-informasi mengenai fungsi negara dibuat agar bisa diakses sehingga aktifitas-aktifitas negara menjadi subyek untuk dikritisi dan mendorong opini publik. Pada tahap ini, ruang publik dirancang untuk sebuah mekanisme institusi untuk merasionalisasikan dominasi politik dengan memberikan tanggungjawab negara pada warganegara (Kadarsih, 2008).
Ruang publik milik siapa?
Konsepsi Habermas di atas mengindikasikan bahwa ruang publik dapat diakses oleh siapa tanpa monopoli satu pihak apalagi monopoli Negara. Sebagai arena produksi dan reproduksi diskursus, Negara tidak boleh melakukan pengendalian terhadap ruang public secara berlebihan. Eksploitasi ruang publik oleh sekelompok orang justru mengerdilkan esensi demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan selama ini, bagaimana tidak ruang public yang seharusnya menjadi arena bertumbuhnya informasi yang mencerdaskan justru diisi oleh informasi-informasi yang tidak produktif seperti pernikahan artis yang memang diproduksi informasinya secara besar-besaran. Sementara rakyat yang seharusnya menjadi pengisi wacana dalam ruang publik terpinggirkan oleh ketakutan menyampaikan kebenaran atau bersuara dalam posisi yang sedikit berbeda dengan penyelenggara kekuasaan dan partai politik. Ketakutan rakyat bukan tanpa alasan, sebab menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan kekuasaan akan dihajar habis-habisan oleh “buzzer” yang sepertinya memang dipelihara oleh mereka yang berkepentingan.
Perebutan ruang publik di tengah pandemic covid 19 semakin menguat, paling tidak ditandai oleh semerbaknya informasi yang berasal dari atas (Negara dan elit) dan juga informasi dari bawah (rakyat). Dengan melihat tampilan informasi yang berkembang dewasa ini, tampaknya ruang publik begitu didominasi informasi dari atas, ini khususnya ruang publik pada media-media mainstream. Sementara informasi dari bawah (rakyat) justru lebih banyak menyasar pada media-media sosial yang kadang hanya menjadi asesoris informasi (bukan informasi utama). Sederhananya, untuk mengembangkan diskursus saja rakyat sangat kesulitan lebih-lebih mengembangkan wacana kebijakan yang berbeda dengan kekuasaan.
Monopoli elit dan dominasi Negara
Pada beberapa kasus, informasi-informasi yang disajikan dalam ruang publik justru dianggap liar dan tidak berdasar (hoaks). Seharusnya, tugas Negara menyaring informasi itu agar memiliki dasar yang jelas. Konsumsi informasi yang tidak jelas justru akan mengecilkan makna hadirnya Negara dalam mengatur alur masuk dan keluarnya informasi, Negara tidak boleh menjadi pengendali melainkan sebagai pengatur. Publik (rakyat) mestinya mendapat sajian informasi yang edukatif bukan melulu informasi entertainmen. Namun akhir-akhir ini, tampaknya persoalan rating justru lebih dikedepankan daripada soal konten edukatif dan dalam hal ini tampaknya Negara sedikit kalah dari media.
Selain sajian informasi yang entertain, nyatanya ruang publik dewasa ini juga dimonopoli oleh elit. Bagaimana tidak, elit-elit itu mampu menggelontorkan anggaran untuk membeli media atau sekedar membeli berita dan produksi dari media terhadap berita itu dilakukan secara besar-besaran. Kontrol Negara seolah tidak bermakna mengingat informasi yang disajikan kadang juga direstui oleh Negara (penguasa). Padda akhirnya, yang menjadi korban dari disinformasi di ruang public itu adalah rakyat.
Kepada siapa berharap?
Monopoli ruang publik oleh elit dan kelompok artis memang membuat berbagai kelompok masyarakat di aras bawah begitu “jengkel”. Informasi-informasi edukatif durasinya tidak sebanding dengan informasi yang non edukatif, gejala ini memang dampak dari perkembangan ekonomi-politik media dan demokrasi popular yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pandemi covid 19 telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap informasi, melalui media sosial dan perangkat gawai yang hampir dimiliki oleh setiap rumah tangga bisa saja informasi berkembang menjadi “viral” walaupun informasi itu belum tentu teruji kebenarannya.
Publik hanya berharap pada kebijaksanaan Negara (penguasa) agar fungsi pengaturan dijalankan dengan baik, juga berharap kepada Dewan Pers untuk dapat melakukan fungsi edukasi agar informasi yang tersaji di ruang public lebih banyak memuat konten-konten edukatif dan menjadi penyeimbang antara konten dari atas dan konten dari bawah.
Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta