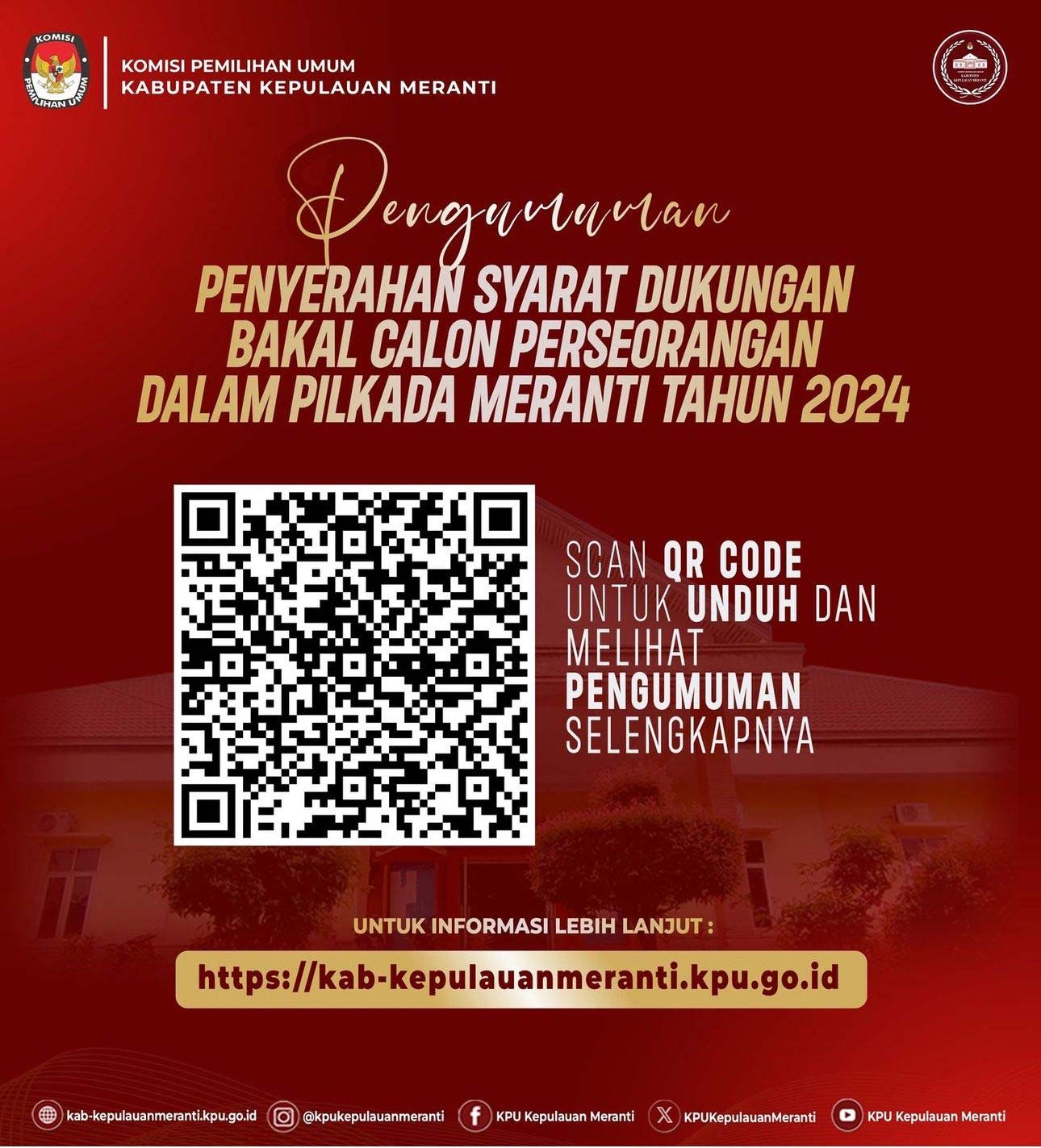PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Bencana kabut asap yang melanda Riau dan sekitarnya dirasakan semakin pekat dan sesak oleh warga terutama mulai awal September 2019. Praktik land clearing yang dilakukan oleh oknum-oknum ‘pembantai’ ekosistem masih menjadi pilihan utama pembersihan lahan, hanya semata tuntutan ekonomi dan target keuntungan sebesar-besarnya. Sampai dengan tulisan ini dibuat setidaknya Polda Riau telah menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus karhutla, dan baru 4 korporasi menjadi tersangka. Padahal pihak KLHK mengklaim telah menyegel 42 perusahaan yang diduga menjadi otak pembakaran hutan dan lahan dalam rangka proses hukum.
Berbagai upaya preventif sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya bencana karhutla. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Inpres No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Sesungguhnya Inpres ini telah lama dinanti oleh berbagai pihak terutama praktisi pengusaha perkebunan sawit dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Penantian ini tentunya bukan tanpa sebab atau tanpa alasan yang kuat.
Beberapa permasalahan yang menjadikan moratorium perizinan sawit ini menjadi sangat urgen dan dinanti-nanti oleh berbagai pihak diantaranya adalah: Pertama, bahwa persoalan perizinan sawit telah lama memunculkan konflik sosial yang dipicu oleh masalah sengketa penguasaan lahan. Berdasarkan data Sawit Watch, luas perkebunan sawit di Indonesia sudah mencapai 22,2 juta hektare. Konflik agraria di perkebunan sawit sepanjang tahun terus meningkat. Hingga kini, ada 750 konflik di perkebunan sawit.
Kedua, telah terjadi tumpang tindih dalam perizinan terkait HGU, seringkali perizinan dikeluarkan tanpa adanya pengecekan di tingkat lapangan. Kondisi ini memunculkan status baru yakni tumpang tindih aturan maupun produk turunan dari aturan-aturan yang tumpang tindih tersebut. Terutama di areal yang masuk dalam kawasan alokasi penggunaan lain.
Ketiga, masalah yang paling serius sesungguhnya adalah masalah lingkungan yang eskalasinya semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pembukaan lahan terutama kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
Carut marutnya pengelolaan perkebunaan kelapa sawit di Indonesia memerlukan penyelesaian permasalahan dengan cara dan proses yang tidak sederhana mengingat permasalahan tersebut sudah melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Solusi terhadap berbagai permasalahan di atas pada dasarnya dapat dikembalikan pada solusi tiga langkah reformasi, yakni reformasi paradigma ekonomi pengelolaan sumber daya alam, reformasi kebijakan, dan reformasi implementasi teknis.
Pada tataran paradigma ekonomi pengelolaan SDA, saat ini cara berpikir terhadap pemanfaatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan masih di-drive oleh asas manfaat dengan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam hal materi atau nilai rupiahnya. Terbukti dari pernyataan beberapa pihak tentang bagaimana untuk senantiasa meningkatkan produksi sawit dari peluang pemanfaatan lahan dan pasar yang ada. Padahal nilai kehilangan manfaat lingkungan (loss of environtment benefit) juga sangat besar. Maka perlu dilakukan penelitian secara lebih detail dan mendalam terkait nilai kehilangan manfaat lingkungan ini, untuk menentukan perhitungan secara cermat, berapa besar atau luas perkebunan kelapa sawit yang dapat dibuka. Paradigma mengejar manfaat ekonomi (rupiah) harus diganti dengan paradigma pemanfaatan secara bijak dengan menyeimbangkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Salah satu manfaat lingkungan dari hutan dan vegetasi adalah kemampuan menyerap dan menyimpan karbon.
Semangat solusi yang kedua adalah semangat reformasi kebijakan. Moratorium sawit oleh pemerintah saat ini dinilai tepat oleh beberapa pihak, namun perlu ada pertimbangan yang lebih mendalam terkait jangka waktu pelaksanaannya yang hanya tiga tahun. Sebagian pihak menilai 3 tahun adalah waktu yang cukup, namun sebagian pihak mengatakan masih terlalu singkat, bahkan ada yang mengusulkan untuk diperpanjang hingga 25 tahun.
Menurut penulis, moratorium selama 3 tahun memang masih sangat singkat mengingat kompleksnya permasalahan yang ada. Dengan memasukkan pertimbangan adanya masa-masa transisi atau proses pemilu Presiden dan legislator, maka jangka waktu minimal 7 tahun adalah cukup obyektif dan optimis bagi pelaksanaan moratorium perizinan sawit. Selain jangka waktu pelaksanaan, sebagai konsekuensi dari semangat reformasi paradigma pertama di atas, maka pemerintah perlu terus mengarahkan focus fasilitasi pada perkebunan sawit masyarakat di lahan-lahan non kehutanan, maupun kawasan kehutanan yang kurang produktif (telah rusak). Sebagaimana diketahui saat ini perkebunan sawit mayoritasnya adalah dikuasai oleh swasta sebagai pemegang konsesinya, sebagian dari lahan tersebut ternyata berada di dalam kawasan hutan. Maka perlu ada peninjauan kembali terhadap lahan-lahan tersebut.
Ekspansi perluasan sawit swasta lebih disebabkan oleh faktor mengejar keuntungan finansial sebesar-besarÂnya. Bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan disinyalir juga diakibatkan oleh watak rakus dari para korporasi ini. Dengan pergeseran titik prioritas perhatian pemerintah pada masyarakat dalam pengelolaan sawit dan moratorium perizinan sawit dalam jangka yang cukup lama (minimal 7 tahun), diharapkan akan menyeimbangkan timbangan pengelolaan sawit dari swasta ke masyarakat. Sementara pihak swasta dapat didorong untuk lebih mengutamakan pada industri pengolahan sawit menjadi produk-produk turunan yang siap konsumsi dan ekspor, bukan dalam bentuk CPO. Pola ini sesungguhnya telah berjalan pada sektor perkebunan yang lain seperti kopi dan kakao.
Semangat yang ketiga adalah reformasi teknis implementasi kebijakan. Setidaknya ada tiga hal yang dapat membantu teknis pelaksanaan kebijakan. Yakni 1) memperkuat kebijakan satu pintu wewenang pemberian izin, 2) adopsi strategi jangka benah untuk sawit yang masuk kawasan hutan, 3) mendorong penelitian terkait peningkatan produktifitas sawit secara intensif bukan ekstensif serta promosi dan sosialisasi komoditas alternatif pengganti sawit.
Kebijakan satu pintu pemberian izin perlu diperkuat dengan mengintegrasikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberian izin, seperti Pemda, KemenLHK, Kementan, Kemenko Perekonomian, BPN dan pihak keamanan.
Penelitian terkait komoditas lainnya sebagai pesaing sawit juga sangat mendesak untuk dilakukan. Komoditas lain seperti geronggang, aren dan MPTS lainnya perlu didorong untuk memperoleh pasar yang layak, sehingga perlu dukungan penelitian lebih jauh lagi, dan pada gilirannya akan mampu menjadi komoditas pesaing sawit sekaligus berangsur-angsur mampu menggantikan sawit yang kurang ramah lingkungan, dengan komoditas yang ramah lingkungan. Hasil-hasil penelitian oleh lembaga litbang KLHK maupun Pemda dapat dielaborasi lebih jauh lagi untuk diadopsi sebagai langkah teknis pencegahan dan penanggulangan karhutla.***